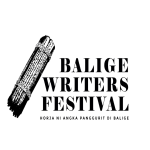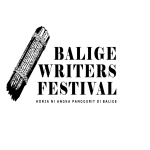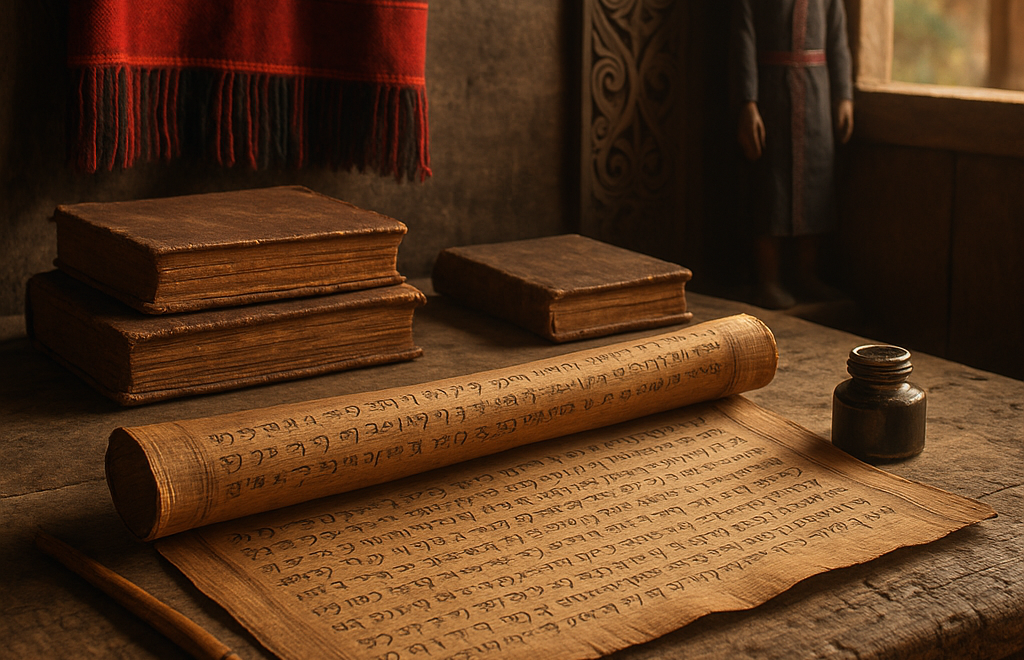
Bulan Desember: Kala Para Perantau Pulang Kampung
Balige tahun 80-an menyimpan kisah hangat tentang pertemanan, mimpi merantau, dan citra si "sukses dari kota" yang selalu pulang bergaya. Bagi kami remaja SMA saat itu, para perantau adalah simbol keberhasilan—berpakaian necis, bersepatu putih mengkilap, belanja roti di Terang Bulan, martandang ke rumah si bunga kota, lalu gandengan tangan ke bioskop Maju atau Antara. Saya hanya bisa bermimpi: kapanlah saya bisa seperti mereka? Namun, waktu berjalan dan saya pun merantau. Hidup di ibu kota tidak seindah bayangan. Perjuangan keras kuliah sambil bekerja, tinggal di gang sempit, membuat saya menyadari: di balik glamornya gaya si perantau, banyak dari mereka adalah sopir, pedagang kaki lima, bahkan calo terminal yang hanya ingin tampil "wah" saat pulang kampung. Kini, Balige telah berubah. Kota makin maju, mobil dan motor bukan lagi barang langka. Tapi yang hilang perlahan adalah rasa holong (cinta) antar teman. Tak ada lagi sambutan heboh untuk si perantau. Kadang rasa segan muncul saat pulang. Namun, duduk bersama di lapo tuak, membahas masa kecil, cerita bolos sekolah dan berburu harimonting, semua rasa canggung itu bisa cair kembali.
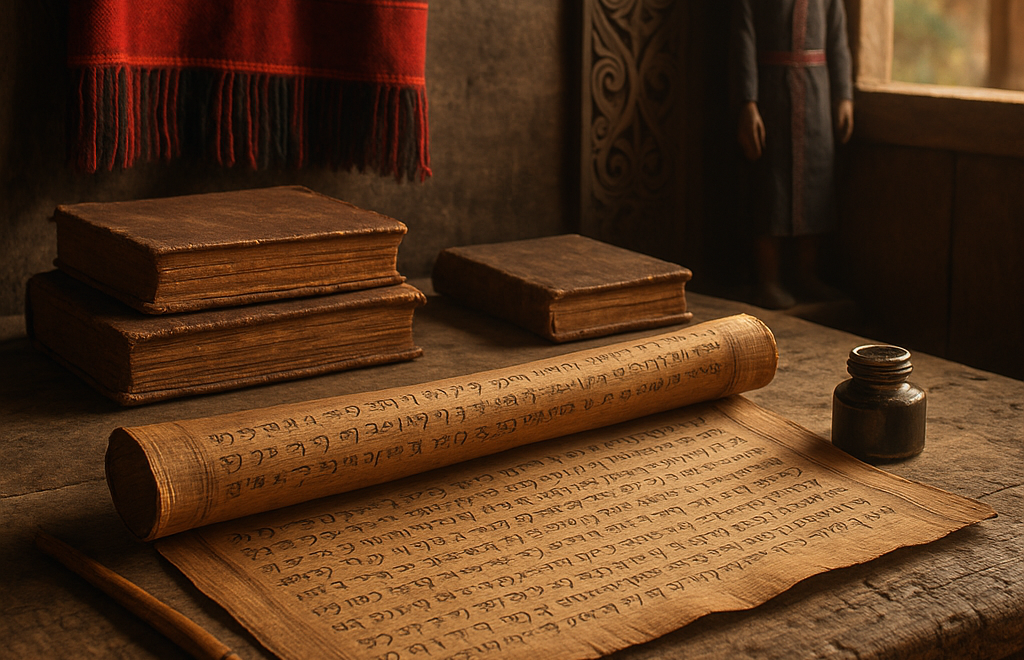
Balige Kota Kreatif
Balige di tahun 1980-an adalah panggung kreatif yang hidup dalam kenangan masa kecil saya. Ketika teknologi belum merajai dunia, kota ini sudah menampilkan kreativitas warganya melalui liturgi Natal, latihan koor, drama jalanan, hingga permainan sederhana yang diciptakan sendiri. Anak-anak tampil percaya diri di gereja, bernyanyi dalam harmoni, menari dengan kostum dari sarung ibu, hingga menciptakan stik golf dari batang ketela. Dari sup hangat Mak Riang hingga harimonting ungu yang dikudap tanpa dicuci, semua menjadi bagian dari ekosistem budaya yang tumbuh alami. Balige bukan sekadar kota kecil, ia adalah ruang kreatif, tempat imajinasi dan tradisi bertemu, jauh sebelum istilah “kota kreatif” menjadi tren.